Setidaknya dalam empat dasawarsa terakhir, ada euforia di kalangan Muslim sejagat tentang ‘kebangkitan peradaban Muslim’; atau bahkan ‘kebangkitan Islam’.
Meski ada pencapaian- pencapaian tertentu yang membuat kalangan Muslim bisa optimis tentang ‘kebangkitan peradaban’ tersebut; tapi dalam segi-segi lain, cukup banyak pula gejala dan kecenderungan yang membuat pandangan tersebut boleh jadi lebih sekedar retorik daripada kenyataan.
Refleksi penulis kertas kerja ini tentang perkembangan peradaban Muslim pada masa kontemporer itu menguat setelah pernah mengikuti diskusi terbatas Institute for the Study of Muslim Civilization (ISMC), Aga Khan University, London, 29 Mei 2008.
Memang belum ada evaluasi dan assessment yang komprehensif tentang kondisi peradaban Muslim dewasa ini; tetapi setidak-tidak sejumlah observasi telah dilakukan banyak kalangan, khususnya para ahli peradaban Muslim sendiri.
Secara demografis, jumlah kaum Muslimin meningkat secara signifikan pada tingkat internasional. Diperkirakan jumlahnya lebih dari 1,9 milyar jiwa (2022); berarti merupakan masyarakat agama kedua terbesar setelah Kristianitas (Katolik dan Protestan digabungkan). Dan peningkatan itu, terutama sebagai hasil dari pertumbuhan kelahiran, karena masih banyak kaum Muslimin yang tidak menjalankan keluarga berencana.
Dengan jumlah yang terus meningkat itu, kaum Muslim pada dasarnya memiliki potensi yang kian besar pula; tidak hanya untuk membangun peradaban Muslim, tetapi juga pada peradaban dunia secara keseluruhan.
Tetapi potensi itu belum bisa diwujudkan. Jumlah penduduk Muslim yang begitu besar belum dapat menjadi aset, tetapi sering lebih merupakan liabilities.
Hal ini tidak lain, karena kebanyakan penduduk Muslim tinggal di negara-negara berkembang; atau bahkan di negara-negara terkebelakang, yang secara ekonomi menghadapi berbagai kesulitan berat seperti kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat seiring meningkatnya krisis enerji dan krisis pangan dunia.
Lebih daripada itu, dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak menentu, pendidikan di banyak kalangan kaum Muslimin bukan hanya tidak kompetitif vis-a-vis masyarakat lain, tetapi bahkan sering di bawah standar.
Bukan hanya itu, banyak anak tidak mendapatkan pendidikan; terpaksa mengalami putus sekolah, yang akhirnya membuat mereka tidak punya masa depan untuk memajukan diri sendiri, apalagi peradaban Muslim dan peradaban dunia.
Memang ada negara-negara Muslim kaya berkat minyak, yang mendatangkan windfall terus menerus karena kenaikan BBM yang terus pula terjadi.
Tetapi pada segi lain, windfall tersebut justru menambah beban negara-negara Muslim yang tidak atau kurang memiliki sumber alam BBM; sebaliknya mereka harus mensubsidi negara-negara kaya minyak tersebut. Dan windfall yang diperoleh negara-negara Muslim kaya minyak itu tidak mengalir ke negara-negara Muslim miskin dalam bentuk grant atau investasi; jika ada, jumlahnya tidak signifikan, boleh dikatakan hanya berupa tetesan (trickle) belaka.
Karena itulah negara-negara Muslim yang miskin atau tengah berkembang harus mengandalkan sumber-sumber lain; termasuk menambah hutangnya dari negara-negara atau lembaga-lembaga keuangan Barat seperti World Bank, IMF dan sebagainya.
Keadaan ini tidak bisa lain hanya menambah ketergantungan pada pihak Barat, yang pada gilirannya memiliki implikasi ekonomis, politis, dan bahkan psikologis di kalangan umat Muslimin.
Salah satu dampak psikologis itu adalah menguatnya sikap mental konspiratif; bahwa para penguasa negara-negara Muslim berkolaborasi dengan pihak Barat, misalnya saja, untuk mengembangkan ekonomi pasar yang liberal di negara-negara Muslim dengan mengorbankan potensi-potensi ekonomi dalam masyarakat Muslim sendiri.
Dampak lebih lanjut dari psikologi konspiratif ini dengan segera mengalir ke dalam kehidupan politik, dalam bentuk ketidakpercayaan pada rejim yang berkuasa, yang pada gilirannya mendorong berlangsungnya instabilitas politik terus menerus di banyak negara Muslim.
Psikologi konspiratif lebih jauh lagi membuat kalangan Muslim—khususnya sebagian ulama, pemikir dan aktivis Muslim—terperangkap ke dalam sikap defensif, apologetik dan reaksioner; terpenjara ke dalam enclosed mind atau captive mind, mentalitas tertutup yang penuh kecurigaan dan syak wasangka.
Akibatnya kalangan Muslim seperti ini lebih asyik pula dalam masalah-masalah furu’iyyah, baik dalam bidang sosial, budaya, pemikiran dan keagamaan. Buahnya adalah keterjerambaban ke dalam tindakan dan aksi-aksi yang kurang produktif dalam upaya memajukan peradaban Muslim.
Karena itu, jika kita mau berbicara tentang kemajuan peradaban Muslim, sudah waktunya kaum Muslimin membebaskan diri dari psikologi konspiratif dan enclosed mind.
Pada saat yang sama lebih menumbuhkan orientasi ke depan daripada romantisme tentang kejayaan peradaban Muslim di masa silam. Tak kurang pentingnya, kaum Muslimin seyogyanya lebih mengkonsentrasikan diri pada upaya-upaya kreatif dan produktif daripada terus dikuasai sikap defensif, apologetik, dan reaksioner yang sering eksesif.
Prasyarat Kebangkitan
Kembali pada hal ‘kebangkitan peradaban Islam’, apakah kebangkitan China dan India juga bakal mengimbas dan mendorong kebangkitan peradaban Islam yang juga berporos di Asia Tenggara dengan Indonesia dan Malaysia sebagai motornya?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu berbicara tentang beberapa prasyarat bagi kebangkitan peradaban yang kontributif bagi peradaban dunia secara keseluruhan.
Prasyarat utama adalah stabilitas politik. Demokrasi Indonesia yang telah diadopsi dan dipraktekkan sejak 1999 masih perlu dikonsolidasikan dalam tiga hal: basis konstitusional-legal, kelembagaan (parpol, legislatif dan eksekutif), dan budaya politik.
Hanya dengan konsolidasi lebih lanjut dapat ditegakkan good governance, penegakan hukum, dan kohesi sosial.
Sedangkan di Malaysia juga mendesak perlu konsolidasi kekuatan politik umat Islam yang tercerai-berai dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan untuk mempertahankan hegemoni politik dan kekuasaan Melayu baik di eksekutif maupun legislatif. Juga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang mutlak perlu bagi kemajuan puak Melayu khususnya.
Konsolidasi demokrasi dan politik di kedua negara berpenduduk mayoritas Muslim ini mutlak untuk pembangunan peradaban utama juga meniscayakan partisipasi publik dalam proses politik demokrasi dengan segala ekses negatif yang sudah sampai pada titik yang tidak bisa dimundurkan lagi (point of no return).
Tetapi juga jelas, proses politik demokrasi di Malaysia dan Indonesia masih menyisakan banyak masalah, sejak dari fragmentasi politik, kepincangan politik, oligarki politik, korupsi, tidak fungsionalnya check and balances dan seterusnya. Pendidikan jelas merupakan prasyarat mutlak bagi kebangkitan peradaban Islam.
Untuk dapat menjadi tulang punggung kebangkitan peradaban, pendidikan Malaysia dan Indonesia bukan hanya harus mencapai pemerataan (equity), tapi juga harus semakin berkualitas sejak dari tingkat dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Hanya dengan pendidikan seperti itu, kaum muda negeri ini dapat bertransformasi bersama menuju kemajuan peradaban.
Dalam konteks itu, pendidikan tinggi khususnya harus dikembangkan tidak hanya menjadi sekadar teaching higher institution—atau universitas pengajaran—tetapi sekaligus menjadi research institution. Proses pendidikan di perguruan tinggi sudah waktunya berbasiskan riset (research-based education).
Prasyarat tak kurang pentingnya adalah pemberdayaan kembali masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat kewargaan atau civil society. Karenanya, salah satu agenda pokok yang harus dilakukan secara berkelanjutan adalah pemberdayaan kembali masyarakat madani yang selama ini bukan tidak mengalami disorientasi karena proses politik manipulatif dan divisif.
Masyarakat madani di kedua negara ini memiliki peran dan leverage yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Masyarakat sipil hendaknya terus berdiri di depan dalam pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan peradaban utama yang demokratis dan berkeadilan.
Salah satu kunci pokok lainnya dalam pembentukan peradaban utama adalah pengembangan dan peningkatan keadaban masyarakat (public civility). Dalam disrupsi sosial- kultural sebagai dampak tidak diharapkan dari Revolusi 5.0 kita menyaksikan semakin merosotnya keadaban publik dalam bentuk pelanggaran hukum, rendahnya disiplin masyarakat, dan seterusnya.
Banyak kalangan terlihat tidak lagi malu melakukan hal bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaban publik. Pemerintah dan masyarakat sipil atau masyarakat madani (Civil Society) sepatutnya memberikan perhatian khusus pada penegakan kembali etika dan keadaban publik.
Hanya dengan keadaban publik yang kuat, negara Indonesia dapat maju, berharkat, dan berperadaban. Peradaban jelas tidak bisa maju dan hanya bisa terbentuk jika negara-bangsa Indonesia dan Malaysia memiliki tingkat kemajuan ekonomi berkeadilan.
Selama masih banyak bagian masyarakat Muslim yang miskin dan dhuafa, jelas sulit berbicara tentang peradaban utama. Dalam konteks itu, Indonesia khususnya patut terus meningkatkan usaha pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang sering dianaktirikan sebagai sektor ‘informal’.
Memang selama ini pemerintah telah berusaha dan bergerak dalam bidang ini, tetapi tampaknya belum banyak hasil yang dicapai, karena masih saja ada sekitar 40 sampai 50 juta penduduk miskin.
Karena itu pemerintah perlu melakukan berbagai terobosan baru dan mengambil kebijakan afirmatif untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan; membantu pengembangan berbagai usaha kecil dan menengah yang melibatkan banyak warga Indonesia. Kebangkitan peradaban juga memerlukan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bertanggungjawab.
Sejauh ini, kekayaan alam di Indonesia dan agaknya juga di Malaysia cenderung dieksploitasi secara tidak semena-mena dan tidak bertanggungjawab. Akibatnya muncullah berbagai bencana sejak dari banjir bandang, banjir besar, kebakaran hutan, bencana asap dan seterusnya.
Dalam konteks terakhir ini, kaum Muslimin di Asia Tenggara perlu memberi contoh tentang penerapan Islamisitas atau nilai-nilai Islam secara aktual dalam penyelamatan alam lingkungan dan sumber daya alam.
Di sini kaum Muslim harus memperkuat integritas diri pribadi dan komunitas, sehingga dapat mengaktualkan ‘Islam rahmatan lil ‘alamin’ dengan peradaban yang juga menjadi blessing bagi alam semesta.
Profil
Azyumardi Azra, CBE, lahir 4 Maret 1955, adalah gurubesar sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Kini dia adalah Ketua Dewan Pers Republik Indonesia (2022- 2025).
Sebelumnya, dia pernah menjadi Staf Khusus Wakil Presiden RI untuk Bidang Reformasi Birokrasi (19 Januari 2017-20 Oktober 2019); anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (GTK) Sekretaris Militer Presiden RI (2014-2019, 2019-2024); Direktur Sekolah PascaSarjana UIN Jakarta (2007-2011, 2011-2015).
Dia juga pernah bertugas sebagai Deputi Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya dia adalah Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (IAIN,1998-2002, dan UIN, 2002-2006).
Memperoleh gelar MA (Kajian Timur Tengah), MPhil dan PhD (Sejarah/Comparative History of Muslim Societies) dari Columbia University, New York (1992) with distinction, Mei 2005 dia memperoleh DR HC dalam humane letters dari Carroll College, Montana, USA.
Dia juga gurubesar kehormatan Universitas Melbourne (2006-9); Selain itu dia juga anggota Dewan Penyantun, penasehat dan gurubesar tamu di beberapa universitas di mancanegara; dan juga lembaga riset dan advokasi demokrasi internasional.
Dia telah menerbitkan lebih 44 buku dan puluhan artikel dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Italia dan Jerman.
Dia mendapatkan berbagai penghargaan: The Asia Foundation Award 50 tahun The Asia Foundation (2005); Bintang Mahaputra Utama RI (2005); gelar CBE (Commander of the Most Excellent Order of British Empire) dari Ratu Elizabeth, Kerajaan Inggris (2010); ‘MIPI Award’, Masyarakat Imu Pemerintahan Indonesia (MIPI, 2014); ‘Commendations’ Kementerian Luarnegeri Jepang (2014); Fukuoka Prize 2014 Jepang (2014); ‘Cendekiawan Berdedikasi’ Harian Kompas (2015); ‘Penghargaan Achmad Bakrie’ (2015); ‘LIPI Sarwono Award’ (2017); bintang pemerintah Jepang ‘The Order of the Rising Sun: Gold and Silver Star’ diserahkan Kaisar Akihito dan Perdana Menteri Shinzo Abe di Imperial Palace, Tokyo, Jepang (2017).
Selain itu, dia termasuk ‘The 500 Most Influential Muslim Leaders’ (2009) dalam bidang Scholarly (kesarjanaan/keilmuan), Prince Waleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, Washington DC dan The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Amman, Yordania di bawah pimpinan Prof John Esposito dan Prof Ibrahim Kalin.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
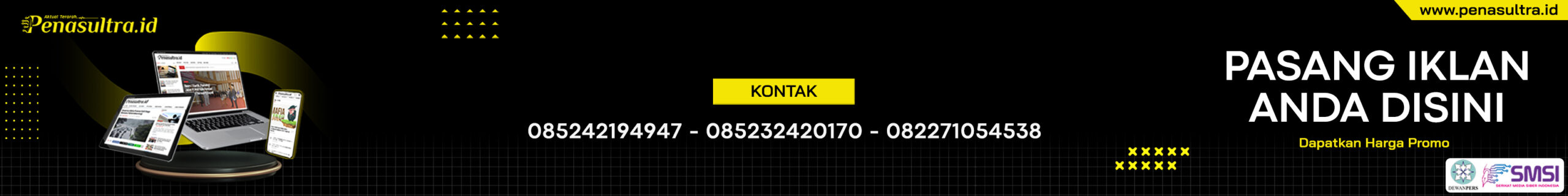

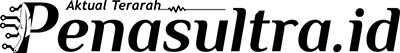




Discussion about this post