Lalu apa yang bisa dilakukan? Hanya dengan tiga cara. Pertama, konfirmasi. Kedua, konfirmasi dan ketiga ya konfirmasi. Lakukan proses ini dengan sebenar-benarnya. Tak bisa dihubungi, ya temui. Tak bisa ditemui ya kejar dimana sumbermu bisa ditemukan. Jangan duduk di warkop, menekan keypad Ponsel lalu karena terdengar panggilan tertolak, atau pesan WA-mu hanya tercentang satu jadi alasan untuk menulis “tak bisa dihubungi”.
Saya ingin berbagi pengalaman saat mengikuti uji kompetensi wartawan, delapan tahun lalu. Saya mendapat tugas menghubungi Kapolda Sultra, demi menanyakan sesuatu. Ini relatif mudah karena sang jenderal, mau mengangkat telepon dan memberi penjelasan meski sebelumnya saya tidak mengenalnya secara personal.
Seorang senior justru mendapat tantangan lebih berat. Diminta menghubungi Gubernur Sultra. Tentu saja sulit tembus langsung. Ia menggunakan cara lain. Ia mulai dengan memastikan posisi gubernur. Setelah informasi ini diperoleh, ia mengidentifikasi siapa saja yang sedang bersama sang pejabat di saat itu. Secara berjenjang, ia akhirnya bisa berbicara dengan gubernur lewat telepon. Begitu caranya.
Beberapa tahun silam, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan di Kota Kendari. Terduga pelakunya dikabarkan tertangkap di sebuah Polsek di Kepulauan Sula, Maluku. Saya ingin mengejar informasi ini, karena ekslusif. Polres Kendari tak berani memastikan apapun, karena mereka baru akan mengecek langsung ke lokasi. Sebagai wartawan, saya ingin mendahului.
Pertama, saya identifikasi dulu posisi Polseknya termasuk dibawah Polres apa. Saya lalu menghubungi orang di Maluku, apakah punya kenalan polisi di Polres Kepulauan Sula. Segala cara diupayakan, secara berjenjang hingga akhirnya saya bisa berbicara dengan pejabat polisi di Polsek itu yang membenarkan adanya tangkapan tersebut. Saat itu belum ada Ponsel pintar, baru Nokia 3310, yang pulsanya mesti 100 ribu sekali isi.
Setidaknya ini menunjukan, dengan keterbatasan sarana komunikasi, upaya konfirmasi itu tetap harus dilakukan dengan cara apapun, dan sesulit apapun. Jangan pernah menyerah lalu mengandalkan “tak bisa dihubungi”. Lalu dengan dalih itu, beritanya kemudian ditayangkan hingga banyak orang ikut menduga, menuding sang pejabat melakukan pelanggaran tanpa ia bisa membela diri di tulisan itu. Zalim namanya.
Kan ada namanya hak jawab? Saya tetap tidak bisa menerimanya. Kenapa? Nantilah saya bahas itu. Saya fokus dulu nonton Indonesia Open, ada partai menarik di sektor ganda campuran.(***)
Penulis: Penyuka Kopi
Jangan lewatkan video populer:
https://youtu.be/oA-ImlcJNQY
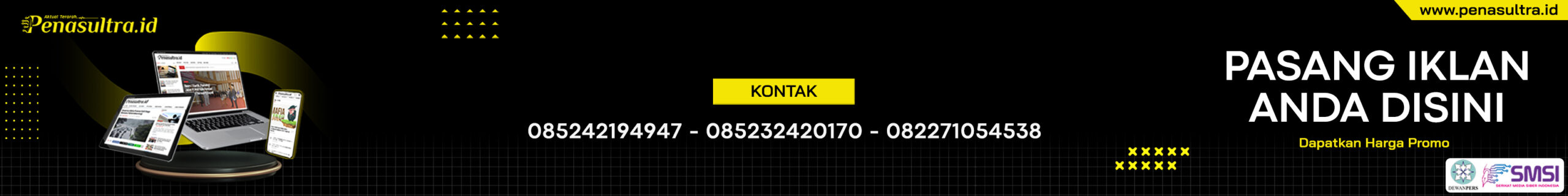

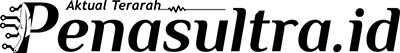




Discussion about this post