Oleh: Hendry Ch Bangun
Pekan lalu Dewan Pers mengeluarkan imbauan agar lembaga negara, swasta, para kepala sekolah dan kepala desa, untuk tidak melayani permintaan bantuan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) terkait Idul Fitri 1443 Hijriah.
Mendadak sontak ponsel saya dipenuhi dengan pesan kalimat dan suara, ditambah menghubungi langsung, karena memang nama saya menjadi narahubung bersama Ketua Komisi Hukum Agung Dharmajaya.
Ada yang mendukung, ini dari unsur pemerintah dan perusahaan, yang selama ini berhubungan dengan wartawan dan media, meskipun meragukan apakah surat edaran itu dipatuhi atau tidak.
Mereka berterima kasih karena setidaknya ada dukungan moral untuk menolak permintaan. Ada juga beberapa wartawan yang mendukung karena di daerahnya banyak orang yang mengatasnamakan pekerjaan wartawan tidak segan-segan meminta THR.
Tetapi lebih banyak yang menghujat dan memaki, karena menilai Dewan Pers kebablasan ikut mengurusi masalah THR.
“Memangnya Dewan Pers menggaji kami, kok seenaknya melarang meminta THR?”
“Dewan Pers melanggar HAM karena menghalangi kami memperoleh bantuan untuk THR”
”Apa kalian di Dewan Pers tahu bahwa kami tidak digaji, mengapa harus menghalangi kami mendapat THR”
“Dewan Pers sendiri pasti meminta THR, jangan sok bersih”
Padahal jelas sekali, THR adalah kewajiban perusahaan pers. Tidak ada urusannya dengan pihak luar. Bukankah pers harus menjaga independensinya dengan tidak menerima apalagi meminta imbalan dari pihak luar?
Saya sempat membalas sedikit, karena waktu saya sedang rapat dan tidak punya waktu untuk membalas semua WA dan pesan suara.
“Anda wartawan? Sudah baca di UU Pers bahwa wartawan itu harus menaati Kode Etik Jurnalistik, dan bahwa di KEJ jelas disebutkan wartawan tidak boleh meminta imbalan dari narasumber?”
Tapi tetap saja mereka ngotot bahwa mereka perlu hidup dan Dewan Pers tidak usah ikut campur terkait urusan permintaan THR karena itu hak mereka.
Dalam hati saya bertanya, siapa orang ini. Apakah mereka benar-benar wartawan atau sekadar begundal yang menjadikan wartawan sebagai pekerjaan untuk hidup? Yang tidak menyadari bahwa profesinya memiliki etika yang sudah jelas mengatur landasan moral dalam bertugas?
Inilah tantangan terbesar bagi masyarakat pers hari ini. Masih sangat banyak wartawan yang tidak memiliki pemahaman –apalagi menerapkan– tentang kode etik jurnalistik, karena asal rekrut dan tidak menjalani pendidikan. Bagaimana mengharapkan karya jurnalistik bermutu dari mereka, sedangkan hal yang sangat elementer bagi profesinya saja mereka tidak tahu?
***
Sepanjang Maret dan April, saya mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di sejumlah provinsi untuk melengkapi hasil wawancara dengan Informan Ahli (IA) dalam rangka Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).
Temuan di beberapa provinsi menunjukkan akibat dari pandemi yang berkelanjutan –yang membuat banyak media mati atau penurunan pendapatan- terjadi penurunan skor pada indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Etika Pers.
Ada pengakuan dari perusahaan pers bahwa mereka terpaksa mengurangi gaji karyawan dan wartawan, ada yang pembayaran ditunda, atau bahkan ada yang melakukan PHK akibat dari kondisi keuangan yang dialami.
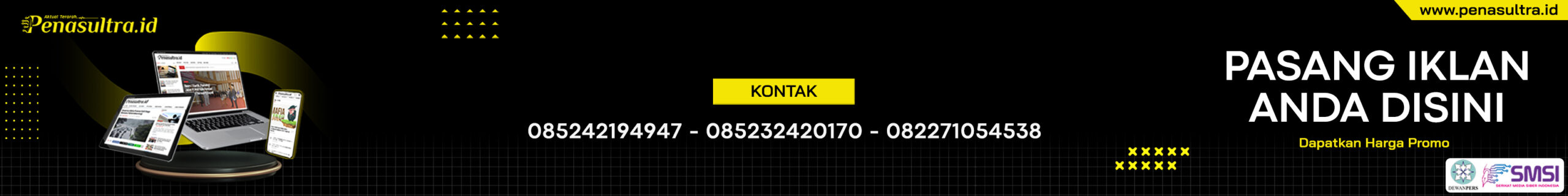

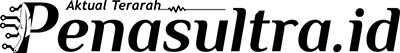




Discussion about this post