Oleh: La Ode Agus Salim Mando
Hutan sebagai salah satu sumberdaya alam Nasional memiliki manfaat secara ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Agar dapat diperoleh aneka manfaat dari keberadaan hutan, maka perlu diselenggarakan secara seimbang, dinamis, dan berkelanjutan.
Namun, kenyataannya kondisi hutan di Negeri ini dari masa ke masa semakin menunjukkan penurunan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
Penurunan kekayaan sumberdaya hutan Indonesia dari aspek kuantitas dapat tergambarkan melalui laporan Badan Pusat Statistik, bahwa luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021, sehingga total luas hutan Indonesia tersisa sekitar 101.215.183 Ha yang berbeda siginifikan dengan data luas hutan pada tahun 2012 yakni 133.574.000 Ha.
Dari aspek kualitas, penuruan kemampuan hutan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjaga kesuburan lahan, menjaga keanekaragaman flora dan fauna, dan lain-lain, juga semakin nyata dengan munculnya berbagai musibah dimana-mana.
Sumberdaya hutan Indonesia mulai dimanfaatkan secara ekonomis untuk menyokong pertumbuhan devisa sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan. Berlakunya ketiga undang-undang tersebut dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan merupakan babak baru terjadinya proses kerusakan hutan di luar Jawa yang berlanjut sampai sekarang.
Dalam beberapa dekade terakhir ini, hak pengusahaan hutan telah termanifestasikan dalam beberapa bentuk perizinan yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK HA/HT/HTR/HKM).
Beroperasinya IUPHHK diikuti dengan anjuran pemberlakukan pemerintah untuk sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayu. Tujuannya untuk menjaga kelestarian hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.
Peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Sedangkan sebagai pedoman pelaksanaannya, pemerintah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Namun, pada pelaksanaannya sertifikasi tersebut tidak berlaku wajib bagi setiap unit manajemen.
Sehingga para pelaku bisnis atau unit manajemen tidak semua melaksanakan verifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayu yang pada akhirnya illegal logging masih terus berlanjut.
Nampaknya, kondisi pengelolaan hutan zaman sekarang, tidak seindah yang terdengar dari sejarah pengelolaan hutan era kompeni Hindia Belanda.
Pencapaian paling mengagumkan dari pengelolaan hutan dikala itu adalah dengan terbangunnya hutan jati seluas 1 (satu) juta hektar di Pulau Jawa yang masuk kategori Bonita 3 (Kelas Produktif).
Prestasi yang demikian gemilang tersebut belum pernah ditorehkan oleh anak negeri sampai sekarang ini. Mengapa hal tersebut terjadi? Inilah yang patut untuk dikaji dan menjadi perhatian bersama.
Hutan di Jawa dahulu dikelola oleh Djatibedrijfs (perusahaan jati) yang merupakan badan hukum milik Negara Hindia Belanda, dimana setara dengan Perhutani sekarang ini. Secara kelembagaan Djatibedrijfs mengorganisir unit manajemen hutan berupa Houtvesterij sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dewasa ini.
KPH pada zaman Belanda dan sekarang khusus di Jawa hampir dibilang tidak berbeda jauh, karena berada di bawah Perusahaan Negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan secara totalitas, termasuk pengaturan keuntungan finansial dan kelestarian hutan.
Hal ini tentu berbeda dengan pembentukan KPH di Luar Jawa yang terkesan kaku atau hanya sebagai fasilitator dari berbagai kegiatan kehutanan maupun non kehutanan.
Awalnya pembentukan KPH membawa angin segar bagi wajah pengelolaan hutan di Indonesia terutama di luar Jawa. Pembangunan KPH merupakan implementasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sumberdaya hutan.
Landasan kebijakan pembangunan KPH diperkuat oleh beberapa Undang-Undang, sedangkan landasan pembangunannya mengikuti beberapa Peraturan Pemerintah dan landasan teknis penyelenggaraannya diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri.
Kebijakan pembangunan KPH adalah usaha konservasi yang dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian, keseimbangan dan pemanfaatan ekosistem sumber daya alam hayati berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Sejak saat itu secara intensif pembangunan KPH dimulai dengan membentuk rancang bangun penetapan lokasi KPH di setiap provinsi.
Langkah itu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan organisasi melalui Peraturan Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 serta dilengkapi perangkat kerjanya melalui pendanaan dari APBN maupun APBD.
Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut diperlukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dengan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Secara konseptual pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berpikir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan Indonesia (Rahmadanty et al., 2021).
Selanjutnya, pembagian kewenangan KPH meliputi: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) menjadi bagian dari pemerintah pusat, sementara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) bagian dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Pembagian kewenangan KPH dalam pengelolaan hutan di provinsi dan kabupaten yang dimaksud disini hanyalah sebatas pada pengelolaan hutan mencakup penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, serta perlindungan dan konservasi alam yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang secara teknis penyelenggaraannya diatur dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Inilah yang menjadi salah satu pemicu belum berjalan efektifnya KPH di luar Jawa. Sungguh sangat disayangkan KPH di luar Jawa sekarang ini, tidak ubahnya seperti lembaga administrator yang mencatat dan memfasilitasi sekian deret perizinan baik itu izin pemanfaatan kayu (IPK), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, hutan tanaman, hutan kemasyarakatan (IUPHHK HA/HT/HTR/HKM).
Bahkan yang lebih parah dari itu adalah hanya sekadar saksi atau pengaman dari adanya pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang jelas-jelas akan mendatangkan kerusakan bagi hutan dalam skala luas. KPH seperti Singa (Raja Hutan) yang lagi letih, lesu dan loyo, jangankan mau melestarikan hutan, menjaga saja hutannya dari perambahan dan pembalakan liar sudah tidak berdaya.


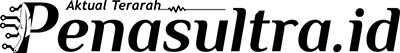




Discussion about this post