Politik Simbolik dan Imajinasi “Persatuan”
Prabowo–Gibran berupaya menampilkan diri sebagai pemersatu bangsa, melampaui polarisasi “cebong–kampret” era Jokowi. Namun, menurut kerangka political symbolism yang ditulis oleh Geertz, C. (2020), tindakan simbolik seringkali membentuk imajinasi harmoni ketimbang harmoni substantif.
Penetapan empat pulau di Aceh–Sumut sebagai wilayah Aceh, misalnya, bisa dibaca sebagai gestur simbolik rekonsiliasi nasional. Tapi di lapangan, keputusan itu tidak disertai dialog struktural dengan masyarakat lokal dan DPRD Sumut. Ini adalah politik simbolik yang meneguhkan citra “presiden pemersatu”, bukan transformasi hubungan pusat–daerah.
Narasi pemersatu yang diusung Prabowo cenderung bersifat vertikal, atau bisa kita sebut sebagai harmoni yang diatur dari atas ketimbang partisipatif. Dalam terminologi Benedict Anderson, ia membentuk imagined community yang dipersatukan bukan oleh deliberasi, tetapi oleh imaji paternalistik tentang negara kuat dan stabil.
Krisis Etika Demokrasi dan Konsolidasi Kekuasaan
Satu tahun ini juga memperlihatkan krisis etika politik, bahwa lemahnya oposisi formal, dominasi partai besar dalam koalisi, dan figur wakil presiden yang sangat muda menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem representasi.
Dalam kerangka polyarchy Robert Dahl, kondisi ini mengurangi responsiveness dan contestability, yaitu dua pilar utama demokrasi. Sementara menurut O’donell, G. A. (2020) gejala ini mencerminkan delegative democracy, yaitu kekuasaan terpusat pada figur presiden yang dianggap mewakili kehendak rakyat tanpa kontrol institusional yang memadai.
Narasi “bapak bangsa” kembali menguat, menggantikan logika check and balance. Dalam konteks ini, demokrasi bukan lagi sistem pengawasan publik, tetapi kepercayaan personal terhadap pemimpin kuat.
Redistribusi atau Reputasi?
Pemangkasan besar-besaran anggaran IKN tampak sebagai koreksi rasional terhadap megaproyek Jokowi. Tetapi tanpa strategi pembangunan alternatif di daerah lain, langkah ini justru bersifat reputational politics, yaitu peneguhan citra “presiden realistis” yang pro-rakyat.
Program MBG pun belum menampakkan keterlibatan signifikan petani lokal dan koperasi desa. Jika rantai suplai tetap dikuasai oleh korporasi pangan besar, maka redistribusi sosial hanya akan menjadi welfare top-down, bukan empowerment bottom-up.
Dalam teori developmental state, redistribusi sejati mensyaratkan transformasi struktural, yang akan membangun kapasitas produksi daerah, bukan sekadar memperluas konsumsi sosial.
Konsolidasi Tanpa Transformasi
Satu tahun pertama Prabowo–Gibran pada dasarnya menunjukkan politik konsolidasi tanpa transformasi. Ia berhasil menata ulang legitimasi, membangun citra kepemimpinan tegas dan populis, serta meredam potensi konflik elite.
Namun, semua itu belum diikuti perubahan struktural dalam tata kelola ekonomi, demokrasi, maupun akuntabilitas publik. Rezim ini tampaknya masih sibuk membangun politik simbol ketimbang politik substansi.
Tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan stabilitas, tetapi mengalihkan logika kekuasaan dari paternalistik ke partisipatif, bahwa dari negara yang hadir di layar televisi menjadi negara yang benar-benar hadir dalam kehidupan rakyatnya.(***)
Penulis adalah peneliti independen dan akademisi yang aktif menulis analisis kebijakan publik dan politik
Jangan lewatkan video populer:


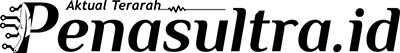




Discussion about this post