“Lalu apa gunanya kami bayar iuran tiap bulan? Tidak semua sopir punya uang tunai untuk biaya darurat,” kesalnya.
Dedi meninggalkan tiga putra. Fatur dan Farhan bekerja di sektor pertambangan, sementara Wahyu, anak bungsunya masih duduk di kelas lima sekolah dasar (SD).
“Wahyu masih menunggu ayahnya pulang malam itu,” kata tetangga almarhum.
“Dia belum tahu arti kehilangan, tapi nanti dia akan mengerti bahwa ayahnya mati karena sistem yang abai,” tambah tetangga almarhum sembari melirik putra bungsu Dedi.
Zulfiani Azis, Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Kendari yang turut mendampingi proses medis di rumah sakit, mengecam keras pelayanan RSUD Bahteramas dan menyerukan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mendengar suara rakyat kecil seperti Dedi. Jangan sampai negara hanya hadir untuk yang kaya dan berkuasa,” sorot Zulfiani.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra La Ode Muhammad Freby Rifai ikut menanggapi kasus ini. Kata dia, pelayanan kesehatan bukan hadiah. Itu hak rakyat.
“Anggaran kita seharusnya berpihak pada rakyat miskin, bukan hanya proyek-proyek mercusuar,” tegas politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Kematian Dedi Wahyudin memang adalah takdir. Tapi perlakuan yang ia terima sebelum meninggal adalah cerminan dari cacatnya sistem.
Ia pergi membawa luka dalam keluarga, namun meninggalkan pesan yang semestinya menggugah bangsa, bahwa kebaikan tidak boleh lagi dikalahkan oleh kekerasan dan birokrasi.
“Kalau orang sebaik Dedi bisa mati tanpa keadilan, bagaimana nasib kita yang lain?,” lirih Yamin, sopir rekan almarhum.
Di negeri ini, kemiskinan sering jadi alasan untuk mengabaikan hak. Tapi kematian Dedi justru menunjukkan sebaliknya, yang miskin pun bisa berteriak, bisa menginspirasi, dan bisa membuat kita bertanya. Apakah sistem ini memang masih berpihak pada manusia?
Penulis: Pyan
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
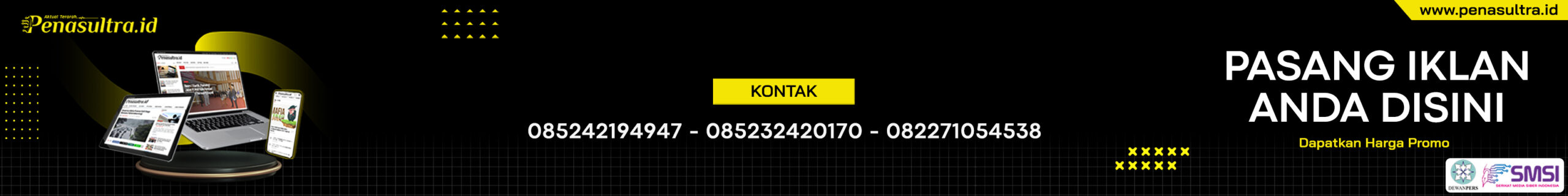

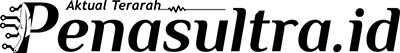




Discussion about this post