Masalah kedua adalah keberlanjutan industri media massa konvensional yang menghadapi tantangan berat. Sumber daya keuangan media semakin berkurang karena sekitar 60% dari belanja iklan sudah disedot media digital terutama platform-platform asing. Memang sebagian perusahaan pers nasional sudah beralih ke media digital, tetapi dominasi platform asing ini telah menciptakan kesulitan.
Isu utama ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data, yang telah menjadi new oil, informasi sebagai tambang kekayaan baru yang nilainya tak terhingga, sehingga masyarakat pers mewaspadai pemanfaatan algoritma.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat,” kata Presiden Jokowi. “Ini harus diwaspadai.”
Dalam berbagai seminar yang diadakan pada tanggal 8 dan 9 Februari, sebenarnya hal-hal yang dikhawatirkan Presiden RI itu dibicarakan dengan mendalam tetapi kalau hanya jadi pembahasan tanpa tindak lanjut, tidak akan ada hasil yang diperoleh.
Terkait media sustainability misalnya, telah dibicarakan di Konvensi Nasional HPN 2020 Banjarmasin tetapi perjalanannya bagai siput, sangat lamban. Satgas Keberlanjutan Media Berkualitas yang dibentuk Dewan Pers berhasil membuat draft pada tahun 2022, meski masih ada persoalan yang belum selesai yakni tentang badan pelaksana apabila aturannya diberlakukan.
Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, seharusnya diberi kewenangan untuk merumuskan tugas fungsi badan pelaksana dan kriteria orang yang akan mengurusnya, bukan yang lain, apalagi wadah perseorangan. Wajar karena Dewan Pers adalah representasi dari konstituen, yakni organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia.
***
Di luar isyu itu, saya sendiri memberikan makalah di Silaturahmi Nasional SMSI pada tanggal 7 Februari di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatra Utama, tentang ancaman eksistensi perusahaan pers skala menengah bawah, terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Dewan Pers No.1 tahun 2023 pada 6 Januari lalu.
Di sini ada kewenangan Dewan Pers untuk mencabut status terverifikasi administrasi atau terverifikasi faktual dari semua media, apabila kontennya dianggap melanggar kode etik dan ada penetapan dari Komisi Pengaduan. Ini aneh bin ajaib. Di UU No.40/1999 saja tidak ada sensor, apalagi breidel terkait isi media, kok Dewan Pers bisa menilai konten dan menjatuhkan sanksi non etik? Apakah pembuat rumusan ini tidak memahami UU No.40/1999?
Ada pula persyaratan bahwa media minimal memiliki 10 karyawan (termasuk wartawan), suatu batasan yang tidak jelas dasarnya. Di daerah banyak sekali media yang berkolaborasi, bergabung untuk saling memberi dan menerima berita, sehingga jumlah wartawan di lapangan 3-5 orang saja untuk membuat liputan khas lokal sedangkan isyu nasional, internasional, olahraga, diambil dari induk sindikasi berita.
Hal lain adalah soal kelayakan fisik kantor. Sebelumnya diatur bahwa perusahaan pers boleh saja memiliki virtual office, karena bagi media siber hal itu normal di era digital sekarang. Yang pasti ada alamat dan nomor atau email kontak, sehingga kalau ada komplain, mudah dihubungi.
Kalau mampu sewa kantor bagus di salah satu gedung di Jalan Sudirman Jakarta, ok saja. Kalau bisa sewa rumah toko, juga silakan. Tetapi kalau mampunya hanya kantor virtual, juga harus diterima dengan wajar. Pers harus adaptif terhadap kemajuan teknologi begitu pula Dewan Pers.
Pers Indonesia selama ini dikenal dengan swakelola, mengatur diri sendiri, tapi Peraturan Dewan Pers No.1/2023 itu memunculkan kembali Departemen Penerangan era Orde Baru dan wajah Menpen Harmoko pun mendadak terbayang di kepala saya. Over regulated.
Apapun itu semoga pers Indonesia dapat bahu membahu memperbaiki diri dan dapat bertahan dalam kehidupan yang semakin sulit. Horas. Mejuah-juah.(***)
Ciputat, 12 Februari 2023
Penulis adalah Wartawan Senior dan Mantan Wakil Ketua Dewan Pers
Jangan lewatkan video populer:
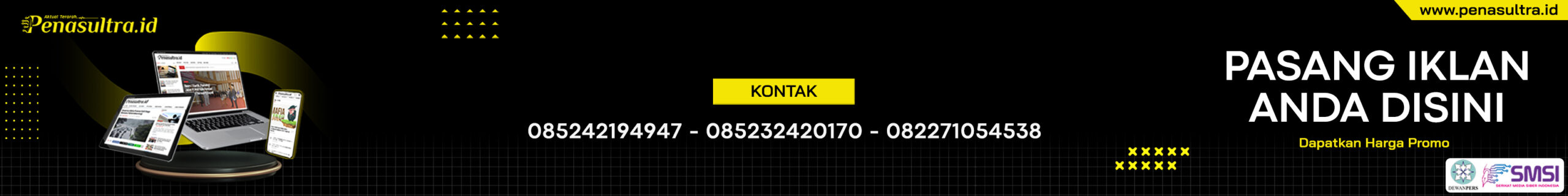

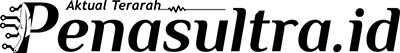





Discussion about this post