Oleh: Rusdianto Samawa
Sidang Majelis Umum PBB mengesahkan secara konsensus resolusi tentang kerjasama antar negara dalam melindungi pelaut (seafarers) pada 1 Desember 2020 lalu. Resolusi yang digagas Indonesia tersebut, mendapat dukungan co-sponsor dari lebih 70 negara dan merupakan resolusi Majelis Umum PBB pertama terkait pelaut dan pengelolaan arus barang secara global (global supply chain).
Hal itu merupakan terobosan penting dalam mendorong perhatian dunia terhadap isu-isu keselamatan pelaut, ABK dan alur supply barang di lingkup maritim, khususnya menyangkut perlindungan pelaut.
Para pelaut diseluruh dunia disebut menghadapi tantangan berat di masa pandemi, di mana restriksi yang ada membuat pergantian awak dan pemulangan pelaut menjadi sulit. Kapal-kapal yang pekerjakan Anak Buah Kapal (ABK), baik domestik dalam negeri maupun luar negeri (Kapal Ikan Asing) sangat sering terjadi kasus eksploitasi terhadap pekerjanya ABK. Memang sangat sering terjadi eksploitasi Anak Buah Kapal: human trafficking, perbudakan dan pelecehan seksual. Negara pun jarang hadir saat terjadi masalah-masalah tersebut. Lebih jauh, belum ada mitigasi (antisipasi) yang baik terhadap perlakuan tidak layak terhadap ABK.
Resolusi Pelaut Indonesia
Regulasi negara untuk melindungi profesi ABK yang rentan eksploitasi. Bahkan, hal ini dianggap seperti biasa Padahal di berbagai negara, kejahatan terhadap ABK selalu terjadi. Parahnya lagi, Indonesia termasuk negara yang parah kondisi ABK-nya. Padahal, perikanan salah satu sektor penting. Output yang dihasilkan sektor perikanan cukup besar untuk memenuhi gizi dan protein, khususnya penduduk Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya.
Harapan pemerintah terhadap upaya resolusi MU PBB tersebut, diharapkan menjadi pendorong kerja sama internasional dalam memfasilitasi pergantian awak kapal, yang merupakan faktor penting dalam pengelolaan arus barang secara global. Adopsi resolusi tersebut secara konsensus tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama negara anggota PBB serta organisasi internasional seperti IMO, ILO dan UNCTAD.
Pada 2016, International Organization for Migration (IMO) bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Conventry University mengeluarkan laporan berjudul Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry. Namun, hasil kerjasama ini tidak kelihatan data faktualnya tentang orientasi, sebab akibat, dan jumlah pasti keberadaan perusahaan perikanan.
Data KKP hingga sekarang, masih memakai data tahun 2011 jumlah tenaga kerja perikanan dan ABK yang bergerak di sektor perikanan tangkap, budidaya, dan pengolah hasil pemasaran sebanyak 11.972.520 orang. Namun jumlah itu, masih belum memadai. Kelemahan data tersebut, Karena kualitas dan kuantitas SDM di sektor kelautan dan perikanan masih lemah.
Saat ini pun, antara jumlah armada kapal ikan nasional dan luar negeri tidak terdata dengan baik berapa sebenarnya jumlah ABK dan pekerja industri perikanan. Sehingga ketika terjadi masalah human trafficking (perdagangan manusia), perbudakan dan pelecehan seksual dalam sektor perikanan, pemerintah sering abai. Karena data faktual tidak dimiliki.
Salah satu inti resolusi dari aturan dan protokol IMO tentang Pergantian Awak Kapal pada pelayaran internasional, yang mendorong negara anggota untuk membuka akses pergantian awak kapal dan repatriasi pelaut. Karena itu, bentuk bukti nyata komitmen komunitas internasional dalam mengatur arus barang global dan keselamatan pelaut. Sebagai salah satu negara penyumbang pelaut terbesar di dunia adalah Indonesia.
Kompas (2020) merilis hasil kajian International Organization for Migration (IMO) dan Conventry University yang mengeluarkan laporan berjudul Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry, terbagi menjadi dua konteks yakni; pertama, mencakup perdagangan manusia (nelayan, ABK dan pekerja migran) untuk keperluan eksploitasi tenaga kerja di laut dan operasi darat.
Aktivitas yang berbasis di laut termasuk penangkapan ikan di kapal, pembudidayaan ikan di instalasi tengah laut, serta mengambil sumber daya laut dari perahu atau kapal. Sementara itu, aktivitas yang berbasis di darat antara lain bengkel kapal, bekerja di pelabuhan (reparasi jaring ikan, memilih ikan atau hewan laut), serta pembudidayaan hewan laut di daratan. Kedua, mencakup perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak, untuk kepentingan eksploitasi seksual bagi nelayan atau pelaut.
Data KKP yang bersumber dari survei BPS tahun 2018 – 2019 bahwa Indonesia terdapat 12 juta pekerja yang harus dipenuhi haknya sesuai UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 2, dan Pasal 28E ayat 1. Jumlah ini, ada peningkatan dibanding tahun 2011 lalu. Tetapi, perlu diketahui dalam konstitusi; UUD 1945 dan Pancasila, bahwa tiap-tiap warga negara (ABK dan Pekerja Industri) berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, memilih pekerjaan, dan terbebas dari ancaman eksploitasi; human trafficking, perbudakan dan pelecehan seksual yang menjadi hak asasinya.
Para ABK dan pekerja industri perikanan hingga saat ini masih berada di bawah sistem kerja outsourcing, beban dan jam kerja yang panjang capai 10 jam per hari tanpa upaya yang layak, tidak dilindungi asuransi, intimidasi, dan pemecatan sepihak. Dari hasil riset Front Nelayan Indonesia (FNI) 2021 dalam masa pandemi covid, pekerja perikanan mendapatkan upah rata – rata mulai dari Rp30.000 – Rp150.000 per hari untuk kapal domestik dan rerata Rp200.000 – Rp250.000 per hari untuk kapal ikan asing (KIA). Jika dibandingkan dengan beban dan resiko kerja yang mereka alami, upah tersebut tergolong sangat rendah dan pelanggaran hak asasi pekerja.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis data tahun 2021 mencatat, bahwa pada 2018 kasus ABK Indonesia di kapal perikanan berbendera asing jumlahnya 1.079 kasus. Pada 2019 capai 1.095 dan tahun 2020 total kasus ada 1.451 laporan kasus. Jumlah kasus tersebut meningkat dalam dua tahun terakhir. Rincian dari 1.451 kasus ABK, 1.211 kasus di antaranya repatriasi, masalah gaji (465 kasus), kekerasan (156 kasus), kematian (70 kasus), TIP (26 kasus), dan lainnya (104 kasus).
Akses Layanan BPJamsostek Lebih Mudah dengan Aplikasi JMO https://t.co/6vepvBOuf6
— Penasultra.id (@penasultra_id) January 24, 2022
Penamaan Kepulauan Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan total luas 8,3 juta km persegi, 17.504 pulau, dan 108.000km panjang garis pantai. Dengan kondisi geografis yang luas tersebut tentunya juga menghadirkan banyak potensi sumber daya yang bisa digali dan perlu untuk dijaga kedaulatannya.
Beberapa waktu lalu, sejak tahun 2017, Delegasi Republik Indonesia (Delri) telah berusaha maksimal mendaftarkan 2.590 nama pulau ke UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke-11 tahun UNCSGN (United Nations Conference on Standardization of Geographical Names) di Markas Besar PBB, New York pada tanggal 7-18 Agustus 2017. Dengan demikian, secara resmi negara berhak memetakkan pulau yang berisi informasi (nama, koordinat dan lokasi) atas berbagai pulau yang telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017, yaitu sebanyak 16.056 pulau.
Jumlah Pulau di Indonesia (termasuk pulau besar dan pulau kecil) yang tertera pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah 17.508 Pulau, namun adanya masalah effective occupation pada 4 Pulau yaitu Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Pulau Yako dan Pulau Kambing menyebabkan lepasnya kedaulatan terhadap Pulau tersebut. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan banyak tindakan dan kegiatan di wilayah perbatasan khususnya di Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Kecil Terluar.
Masih ada 1.448 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi dimasa mendatang. Dengan perubahan cuaca dan berbagai anomali alam, telah terjadi munculnya sejumlah pulau dan hilangnya pulau karena abrasi dan reklamasi. Karena itu, verifikasi pulau dan penamaan pulau terus dilakukan guna mendapat kepastian geografi Indonesia yang terdapat dalam peta dunia. Indonesia mempunyai 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang telah ditetapkan dalam Kepres 6/2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Pada tahun 2019 lalu, pemerintah mengajukan dua area ke PBB, yaitu segmen di utara Papua pada tahun 2019 dan segmen barat daya Sumatera pada tanggal 28 Desember 2020. Sampai saat ini, total area yurisdiksi landas kontinen yang telah diklaim Indonesia kepada PBB adalah seluas 407.966,6 km2. Indonesia kedepankan kepentingan nasional melalui diplomasi maritim di tingkat multilateral dalam pertahankan dan penambahan wilayah dasar laut Indonesia.
Dokumen tersebut meliputi aspek geografis, uji geologi, data, dan metode serta hasil survey di wilayah terkait. Selanjutnya, Badan PBB untuk Batas Landas Kontinen Commission on the Limits of Continental Shelf (CLCS) belum mengambil keputusan berdasarkan data dan argumen yang di sampaikan Pemerintah. Apabila disetujui, maka menambah wilayah dasar laut Indonesia seluas 211,397.7 km2 atau seluas lebih dari 1.5 kali Pulau Jawa dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Indonesia di bidang ekonomi, penelitian, perhubungan, dan bidang-bidang terkait lainnya.
Sangat penting, bagi Indonesia sebagai negara maritim yang mendaftarkan seluruh kenamaan pulau di PBB bagi negara anggota. Tujuannya, menjaga standar penamaan pulau agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda sehingga memudahkan warga negara mengenal pulau diseluruh Indonesia. Namun masalahnya, penamaan pulau tidak serta merta diakui PBB karena pendaftaran nama pulau bukan berarti pengakuan kedaulatan PBB terhadap suatu pulau.
Posisi PBB, khususnya UNGEGN sudah jelas, yaitu hanya menetapkan standarisasi penamaan dan tidak memberikan suatu pengakuan kedaulatan atau pengakuan apa pun tentang status hukum suatu pulau tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dan nama pulau. Hal ini, pertegas otoritas penamaan pulau secara baku sehingga geografis nasional.
Pengajuan perluasan landas kontinen ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2008 untuk wilayah sebelah barat Pulau Sumatera, dan tahun 2019 untuk wilayah sebelah utara Papua. CLCS telah menyetujui pengajuan Indonesia di sebelah barat Pulau Sumatera pada tahun 2011, sehingga Indonesia mendapatkan tambahan area landas kontinen seluas kurang lebih 4,209 km2.


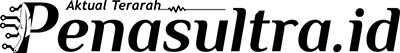




Discussion about this post