Konstatering dalam pelaksanaan eksekusi tanah adalah upaya untuk mengetahui secara pasti apakah jelas atau tidak batas tanah yang hendak dieksekusi. Namun dalam perkara a quo tantangan berat bagi pengadilan adalah menghadirkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) mengingat perkara ini sejak tahun 1993 atau puluhan tahun yang lalu.
Bisa saja para pihak sudah tidak berada ditempat atau telah meninggal dunia. Lalu siapa yang akan menunjuk letak dan batas objek sengketa jika bukan pihak yang berperkara?
Pengadilan mungkin dapat saja menghadirkan Badan Pertanahan selaku instasi terkait, namun menurut penulis pihak-pihak yang terlibat khusus dalam penunjukan letak batas objek sengketa haruslah mengacu pada putusan yakni pihak dalam perkara a quo yakni Penggugat dan Tergugat agar letak batas objek sengketa tervalidasi secara langsung melalui para pihak sedangkan kehadiran Badan Pertanahan tidak lain untuk memetakan letak batas yang ditunjuk oleh para pihak.
Dilain sisi, SHGU yang menjadi dasar penguasaan objek eksekusi telah berakhir sejak tahun 1999 tanpa dilakukan perpanjangan oleh pemegang hak dalam hal ini Koperson (Pemohon eksekusi dalam perkara No 48/Pdt.G/1993.PN.Kdi).
Konsekuensi yuridis dengan berakhir dan tidak diperpanjanganya SHGU oleh pemegang hak adalah hak guna usaha hapus sebagaimana ketentuan norma Pasal 34 huruf a UUPA. Lebih lanjut apabila status bekas tanah SHGU adalah tanah negara maka setelah berakhirnya masa berlaku SHGU, tanah tersebut menjadi tanah negara.
Sejatinya UUPA telah memberikan hak istimewa kepada pemegang SHGU dalam hal untuk memperpanjang keberlakuan HGU, akan tetapi dalam kasus ini pemegang hak tidak mengajukan perpanjangan. Karenanya, menurut pandangan penulis dengan tidak dilakukanya perpanjangan tersebut, haruslah dimaknai bahwa pemegang SHGU telah melepaskan haknya sebagaimana hak keistimewaan yang diberikan oleh UUPA.
Selain itu, menurut penulis, Badan Pertanahan sebagai lembaga berwenang harus secara tegas menyatakan SHGU yang dimaksud telah berakhir dan tidak pernah dilakukan perpanjangan agar carut marut isu mengenai status HGU a quo tidak menjadi bola liar yang tidak berkepastian arah.
Sebagaimana legal issue diatas, menurut hemat penulis dalam literatur ilmu hukum, ada beberapa dasar, alasan dan fakta hukum yang menjadi dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan (non eksekutabel). Di antaranya adalah putusan bersifat deklaratoir, barang objek eksekusi ditangan pihak ketiga, eksekusi terhadap penyewa, tanah yang hendak di eksekusi tidak jelas batas-batasnya, perubahan status tanah menjadi milik negara, dua putusan yang saling berbeda (disparitas).
Mencuatnya isu ketidakpastian hukum, isu ketidakadilan atas status tanah objek sengketa yang digaungkan oleh ribuan masyarakat yang menempati eks SHGU Koperson dalam perkara Koperson vs Wongko Amirudin harus mampu diakhiri oleh Pengadilan selaku lembaga berwenang yang bertindak atas nama hukum dan negara.
Pengadilan harus mampu mengakhiri bola panas atas kasus a quo. Jika tidak, maka akan berseliweran beragam isu. Misalkan isu terkait adanya dugaan mafia tanah dan sebagainya yang saat ini telah menjadi sajian hangat dalam beberapa pemberitaan media.
Berkait ini, penulis meminjam tulisan Prof Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Paul Schloten “hukum itu menyimpan kekuatan pendobrak (exspansiekracht) untuk keluar dari kemandekan, “hukum bukanlah suatu skema yang final (finite scheme) namun terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan”.!!!
Demikian besarnya dampak eksekusi yang rencana akan dilakukan, penulis berharap agar pihak berwenang menggunakan pesan filosofi the blindfolded statue ala Jepang dalam menyelesaikan itu. Bukan dengan pendekatan filosofis the blindfolded statue yang diadopsi dari Barat dengan mata tertutup.
Sebagaimana Prof Achmad Ali dalam tulisan perbincanganya dengan Hakim Agung Jepang (saiko saibansho hanji) “Filosofi apa yang terkandung dibalik “mata tertutup” dan “mata tidak tertutup” itu?
Hakim Agung Jepang menjelaskan bahwa “Dewi Keadilan Barat” yang tertutup matanya, dimaksudkan bahwa penegakan hukum dalam paradigma Barat semata-mata hanya bertujuan untuk menerapkan undang-undang belaka, dan “matanya harus ditutup” untuk segala sesuatu diluar undang-undang tersebut. Mata harus ditutup dari pengaruh moralitas, agama, adat istiadat, kultur, dan sebagainya.
Sebaliknya, “mata penegak hukum Timur” seyogyanya tidak tertutup untuk mampu menyaksikan dan menyerap “rasa keadilan masyarakat”, mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mampu menyerap tuntutan dan aspirasi masyarakat”.
Eksekusi Lahan Tapak Kuda untuk Melindungi Kepentingan Siapa?
Sebagaimana penulis uraikan dalam salah satu legal issue diatas bahwa SHGU yang menjadi dasar penguasaan objek eksekusi telah berakhir sejak tahun 1999, atas dasar itu tentu beralasan jika publik an sich para Justiciabelen tenggelam dalam tanya.
Jika Pengadilan memaksakan kehendak eksekusi maka sejatinya pengadilan sedang melindungi hak hukum siapa? Bukankah dengan berakhirnya masa berlaku SHGU maka telah hilang pula hak penguasaannya? Pertanyaan-pertanyaan publik demikian tidak dapat dihindari ditengah banyaknya sorotan publik terhadap kinerja-kinerja pemerintah saat ini.
Penutup
Legal standing pemohon eksekusi secara formil, ketidakpastian atau ketidakjelasan letak serta batas-batas objek eksekusi dan SHGU yang menjadi dasar penguasaan objek eksekusi telah berakhir sejak tahun 1999 tanpa dilakukan perpanjangan oleh pemegang hak dalam hal ini Koperson (Pemohon eksekusi dalam perkara No 48/Pdt.G/1993.PN.Kdi), dapat dijadikan rujukan dan/atau batu uji oleh lembaga berwenang untuk menyatakan eksekusi dapat dilakukan dan/atau eksekusi non eksekutabel.(***)
Penulis adalah Praktisi Hukum
Jangan lewatkan video populer:
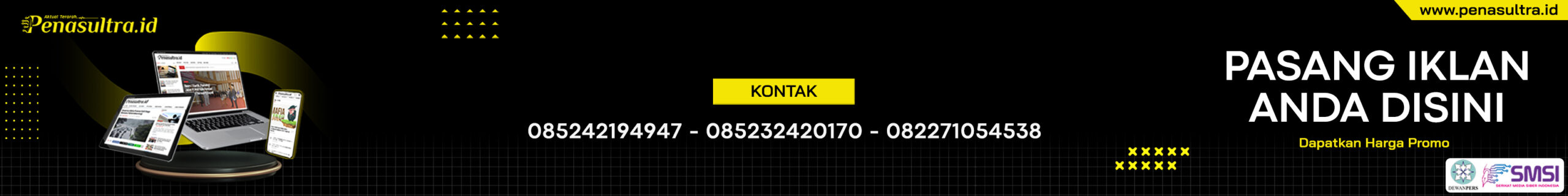

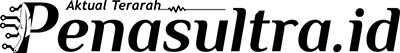




Discussion about this post